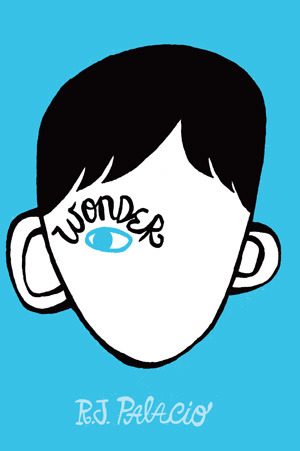Nama perempuan itu Mo.
Kami bertemu di depan sebuah toko buku bekas di dekat rumahku, yang kebetulan juga sejalan ke tempat kosnya. Toko buku itu persisnya bukan sebuah gerai yang menjual buku; malah menurutku lebih persis seperti rumah tinggal sempit berlantai dua, dengan lantai dasar yang dijejali penuh dengan buku, menumpuk di lantai, teras rumah, dan pekarangan tempat sebuah motor usang terparkir. Tamu-tamu yang lewat dapat mencomot sebuah buku yang menarik perhatian begitu saja, kemudian membawanya pulang, dan kembali dengan dua pilihan – membayar dengan harga yang dianggap wajar jika ingin menyimpan temuan mereka, atau mengembalikannya jika tidak puas. Semudah itu. Pada umumnya, buku-buku mengumpulkan debu, atau hanya dibolak-balik pejalan kaki yang iseng dan penasaran.
Buatku sendiri, toko buku itu adalah surga dunia. Aku seringkali menemukan jilid-jilid langka, dijadikan alas gelas atau tempat tidur siang kucing ras kampung milik pemiliknya, Pak Danu. Biasanya aku membayar seadanya, berapa lembar rupiah pun yang kumiliki dalam dompet. Tapi biasanya, Pak Danu cukup bermurah hati untuk menghadiahkannya kepadaku. Buat satu-satunya pelanggan tetap, katanya.
Tapi, akhir-akhir ini tambah satu pelanggan tetap di toko mungil itu. Perempuan yang kerap kali bercelana pendek sobek-sobek, kaus lusuh dan rambut acak-acakan yang tertutup topi baseball merah. Dia lewat setiap sore. Gemerincing gelang kakinya yang riuh selalu membuat kucing Pak Danu mengangkat sebelah telinga sebelum kembali mendengkur halus. Suaranya yang cempreng membuat kucing itu bangkit, menjilati tubuh, dan berlari keluar. Mo akan menghabiskan waktu membaca di ‘rumah baca gratis’ sampai malam, lalu pulang. Begitu setiap hari.
Ketika ditanya kenapa tidak membawa buku-buku pilihannya pulang saja seperti orang-orang lain, dia hanya tersenyum sumringah, memperlihatkan kedua gigi depannya yang besar-besar dan memiliki rongga kosong di tengah. “Nggak. Enakan baca di sini,” kilahnya. Padahal, tempat itu tak ber-AC, apalagi berkipas. Duduk setengah jam di sana cukup membuatku mengipasi diri karena gerah, dan rela bertahan hanya demi kecintaanku pada buku, terutama buku-buku gratis.
Jadilah, dia dan aku berbagi ruang sempit di rumah Pak Danu. Hanya sepetak tanah, dengan ribuan buku-buku tua, dan dua sosok orang yang seringkali tak sengaja berhimpitan, atau bersenggol lengan. Biasanya dia terlalu asyik dalam bacaannya untuk meminta maaf, atau mendongak. Hanya suatu kali, ketika ponselku tiba-tiba berdering di sela sunyi dan derik jangkrik malam, baru dia mengangkat kepala, terlihat seolah baru tersadar dari mimpi manis.
Aku menjawab panggilan dengan terburu-buru, merasa terusik sekaligus tak nyaman karena diamatinya sedemikian rupa. Kurasa mungkin itulah kali pertama dia benar-benar memperhatikanku, orang yang berbagi ruang bersamanya selama berminggu-minggu. Padahal, aku sudah sering terang-terangan memelototinya karena acap kali membaca apa pun yang ada di tangannya keras-keras, atau terbahak ketika melewati paragraf yang lucu.
Saat aku menutup telepon, Mo tersenyum kecil. “Pacarmu, ya?”
Eh. Dia pasti mendengar teriakan wanita itu di telingaku. KAPAN PULANG??! Ibuku memang suka membesar-besarkan masalah.
Aku menggeleng, singkat. Pun tak berniat mengelaborasi gestur itu. Bukannya membaca gerak-gerikku, dia malah mengulurkan sebelah tangan untuk mengangkat buku yang kupegang.
“Heh, kamu baca Mitch Albom?”
Aku menarik bukuku menjauh, tersinggung. “Bukannya semua orang baca Mitch Albom?” Karya terbarunya tentang waktu adalah novelisasi pelajaran hidup yang berharga. Sama seperti The Gift karya Cecilia Ahern, yang sayangnya lebih sering dikategorikan sebagai chicklit ketimbang buku inspirasional yang sensasional.
Kembali ke Mo. Dia mengangkat bahu. “Aku enggak.” Kenapa? “Terlalu berteori. Padahal, hidup nggak ada teorinya, kan?”
“Justru dia berbagi pengalaman, supaya orang lain punya pencerahan yang sama.”
Dia mengerutkan hidung, tak setuju. “Pengalaman hidup setiap orang nggak akan pernah sama, apa pun topiknya. Itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari dari orang lain, apalagi buku. Kita harus melewatinya sendiri, baru bisa mempelajari maknanya.”
Entah bagaimana, diskusi kami berlanjut hingga ke warung bakso di depan toko Pak Danu. Di sela-sela seruputan kuah dan suapan baksonya, Mo masih sempat berargumen tentang petuah dalam buku versus pengalaman pribadi yang (menurutnya) tak terkalahkan. Baginya, membaca buku adalah sesuatu yang menyenangkan, hiburan, bukan untuk mendapat pencerahan.
Debat itu berlangsung empat puluh menit dan empat teh botol dingin kemudian. Dia lebih banyak tertawa dari orang-orang yang kukenal. Ketika tertawa, kepalanya terdorong ke belakang dan suaranya membahana, tanpa kendali dan semu malu yang biasa menyertai tindakan lepas kontrol. Dia melakukannya lagi dan lagi, tanpa merasa perlu untuk meminta maaf. Lucunya, ada sesuatu yang membuatku turut tersenyum saat menyaksikannya.
Dia seorang model. “Bukan model fashion yang di majalah-majalah gitu,” sanggahnya. “Tapi model tangan, kaki, rambut. Apa pun yang bisa dimodelin.” Dia terkekeh lagi. Kalau diperhatikan, bagian-bagian tubuhnya memang proporsional. Jemarinya lentik, seperti milik pianis terlatih. Kakinya cukup panjang, meskipun tubuhnya kecil. Lehernya pun jenjang, seperti seorang balerina. Wajahnya oval, dengan lesung pipit samar di ujung kedua sudut bibir, mata yang ekspresif, dan kulit cerah. Rambutnya sering berganti model dan warna – sesuai pekerjaannya.
Malam itu, kami bertolak ke arah yang berlawanan, dan kali ini mengakhiri pertemuan dengan ucapan sampai ketemu lagi.
**