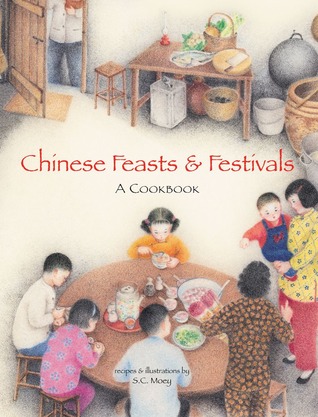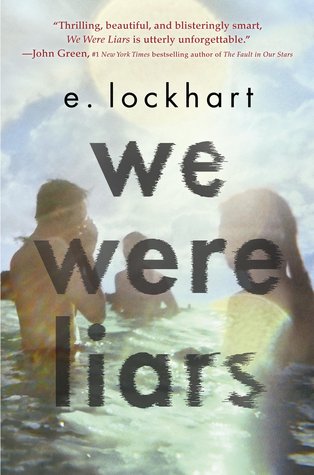Hari ini saya ingin berbagi tentang behind the scene sebuah naskah berkembang menjadi buku yang dipajang di toko-toko dan dijual.
image taken from docstoc.com
Di sini saya hanya berniat sharing pengalaman saya sejauh ini tentang behind the scene buku-buku saya. Buku, penulis dan penerbit yang berbeda tentu memiliki proses yang lain pula, dan kebijakan yang diterapkan tidak selalu sama. Ini juga berlaku bagi saya yang menerbitkan naskah lewat penerbit, bukan self publishing alias menerbitkan buku sendiri.
Pertama-tama, naskah selesai ditulis. And then what?
Biasanya, saya mengirimkan naskah tersebut ke editor yang selama ini sudah menangani buku-buku saya. Jika penulis baru, biasanya mengirimkan printout naskah ke alamat redaksi, ditujukan ke redaksi untuk dibaca dan difilter, apakah naskahnya akan diterbitkan atau dikembalikan.
Pada umumnya, sang editor akan mengabari bahwa naskah sudah diterima dan sedang dibaca. Barulah selang beberapa bulan kemudian, editor akan mengabari 'nasib' sang naskah. Ada tiga pilihan di sini: ditolak, butuh revisi, atau siap jalan. Ditolak berarti naskah tidak akan diproses menjadi buku untuk diterbitkan di penerbit tersebut. Siap jalan berarti naskah siap langsung diproses menjadi buku dan mengikuti berbagai prosedur di penerbit. Seringnya, naskah masuk ke status butuh revisi. Ini berarti, editor akan berkomunikasi dengan penulis tentang berbagai revisi yang dirasa perlu agar naskah lebih maksimal. Misal, dialognya kurang interaktif. Plot ini kayaknya nggak perlu, deh. Ada inkonsistensi di bagian ini, coba diperbaiki. Karakternya kurang berkembang. Dan masih banyak lagi, tergantung naskah tersebut. Nantinya, editor akan memberikan tenggat waktu untuk revisi ini sampai harus dikembalikan lagi ke editor, dan prosesnya terus berlangsung sampai editor merasa naskah sudah oke.
Nah, tahap oke ini adalah yang paling dinanti penulis. Artinya, naskahnya sudah matang dan siap menjalani tahap berikutnya, yakni masuk ke dapur penerbit. Saya pribadi tidak bisa mengaku ahli karena saya bukanlah 'orang dapur' langsung, tapi kurang lebih prosesnya begini:
- Penerbit melakukan rapat internal untuk menentukan jadwal terbit untuk naskah-naskah yang ada. Naskah kita akan diterbitkan sesuai kebijakan penerbit, biasanya pada jadwal yang sesuai dengan berbagai faktor seperti tema promosi, timing yang pas dengan tanggal-tanggal penting atau hari besar tertentu, jangka waktu buku-buku dari penulis yang sama terbit (biar tidak terlalu mepet juga tidak terlalu jauh selisih waktunya), dan lain-lain.
- Tim redaksi akan melakukan editing dan proofreading sembari membuat layout dan kover/sampul buku. Editing dan proofreading dilakukan berkali-kali agar kualitas naskah maksimal, dan bagian estetika juga dipertimbangkan lewat layout serta kover yang cantik, mewakili cerita serta ciri khas penerbit. Di sini, saya membayangkan ada jadwal serta persiapan lainnya yang dibicarakan dengan pihak percetakan dan distribusi, juga tim promosi.
- Setelah naskah selesai diproofread dan sudah memiliki layout serta pilihan alternatif kover, editor akan menghubungi penulis agar kembali membaca dan melihat hasil akhir sebelum dicetak. Biasanya, saya akan membaca kembali naskah tersebut dua kali, dan mengirimkan surel ke editor untuk menandai bagian yang mungkin membutuhkan koreksi, misal ejaan. Editor dan penulis bekerja sama untuk memastikan naskahnya bebas typo, dan semuanya konsisten. Untuk kover, saya ikut voting alternatif kover yang sekiranya tepat untuk si buku, namun pada akhirnya sepenuhnya menjadi hak penerbit untuk memilih. Kenapa? Karena penerbitlah yang paling memahami pasar dan tren, dan mewakili penulis untuk mempersiapkan yang terbaik bagi bukunya.
- Penulis menandatangani surat persetujuan cetak, kontrak buku, dan administrasi lainnya. Menyetujui dan ikut memberi saran dalam penulisan sinopsis/blurb. Menulis ucapan terima kasih, mengirimkan foto dan biodata penulis untuk kover belakang buku.
Lalu, menunggu. Biasanya, setelah tahap terakhir selesai, akan ada jeda sebulan sampai buku selesai dicetak, dan siap dijual di toko buku. Membutuhkan waktu untuk mencetak ribuan sampai puluhan ribu eksemplar buku, belum lagi proses distribusi ke seluruh toko-toko buku Nusantara. Sambil menunggu, tim promosi dan penulis bisa mengobrolkan kegiatan-kegiatan untuk memasarkan bukunya dengan maksimal.
Terkesan sederhana, namun sebenarnya rumit. Saya yakin banyak yang terlewat dari langkah-langkah yang saya tulis di atas, yang mungkin bisa diisi oleh pihak-pihak terkait yang lebih berpengalaman. Tapi, begitulah kurang lebih yang saya lewati. Proses naskah menjadi buku tergantung dari seberapa lama kita merevisi, dan banyak faktor lain. Biasanya, bagi saya memakan waktu kurang lebih enam sampai dua belas bulan.
Bayangkan satu naskah yang mengalami prosedur sedemikian banyaknya, dan kalikan dengan jumlah buku yang harus terbit dalam sebulan. Atau, ratusan buku dalam setahun, atau ratusan naskah yang menumpuk di meja editor. Wow.
Oleh karena itu, setiap buku bukanlah hasil kerja solo seorang penulis saja. Begitu banyak orang yang terlibat di dalamnya untuk menjadikan mimpi itu terwujud, begitu banyak yang berusaha keras agar satu buku bisa terpajang di etalase toko dan siap dibawa pulang oleh pembaca.
So here's to everyone involved - setiap orang dalam perannya adalah penting, dan terima kasih banyak, karena tanpa kalian, naskah hanya akan menjadi seonggok hasil cetakan printer dalam kertas polos.